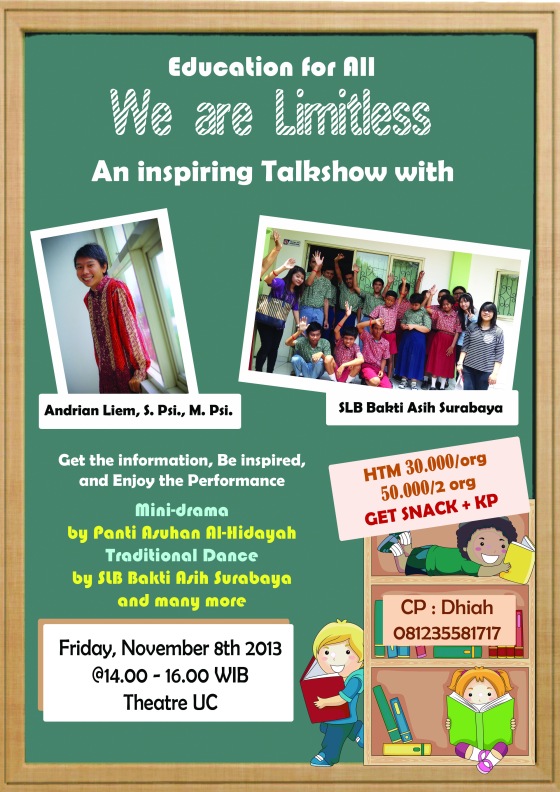Ketika aku bicara soal keyakinan di sini,
Ya, aku berbicara mengenai kamu, Tuhanmu, Agama. “Keyakinan”.
Bukan. Aku bukannya Atheis yang tidak mengakui adanya Penguasa di atas kita.
Justru, aku rasa aku yang paling membutuhkan keyakinan bahwa ”Tuhan itu ada”.
Karena “Tuhan itu ada”, bagiku,
keberadaannya ditentukan oleh bagaimana kita menganggap diri kita “ada”.
Kita adalah bukti eksistensi-Nya.
Makanya, katakan sesuatu. Pikirkan sesuatu. Lakukan sesuatu.
Merasakan bahwa kita “hidup”, sama dengan mengakui bahwa Dia selalu “Ada”.
Sistem dalam keyakinanku adalah sebuah permainan. Visual Novel? Kalau kamu tahu.
Hidup yang dijadikan-Nya bukti ini adalah sebuah permainan.
Kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Tidak memilih juga menjadi pilihan.
Kita dihadapkan pada rangkaian events yang bisa saja muncul,
Ketika kita memilih, Ketika kita tidak memilih, Ketika kita ada di rute A atau F,
Ketika gauge untuk event tersebut terpenuhi.
Ya. Pasti semuanya memiliki ending. Good, Bad, Worst, Best, True Ending.
Bagiku hidup buatan Dia, The Life-Writer, benar-benar membuatku berpikir,
“Such a waste if i couldn’t enjoy this life to the fullest,”
Sama saja dengan membeli game mahal yang langka, tapi kamu tidak memainkannya.
Yang paling aku suka, sekaligus yang paling aku ingin coba hindari dari sistem ini adalah :
kenyataan bahwa kita tidak bisa sendiri.
Setiap manusia adalah player dalam sebuah setting yang sama.
Di saat bersamaan, kita bisa menjadi The Blacksmith, The Adventurer, atau The Witch.
Di saat bersamaan, kita bisa menjadi NPC, Non-player Character.
Di saat bersamaan kita hanya background, invisible dalam hidup orang lain.
Dan di saat bersamaan, kita bisa bertemu dengan main player lainnya,
intertwined and unlocked some routes of our life.
Aku mengagumi sistem ini. Aku mengagumi pertemuan. Aku menghargai tiap-tiapnya.
Termasuk, pertemuanku dengan player ini. Manusia itu.
Keberadaan-Nya sebagai Pencipta dalam sistem ini dan membuatkan rute di mana aku dan manusia itu bersinggungan,
I thank Him. You’re that amazing.
I’m glad i chose this route,
and meeting that human in this system.